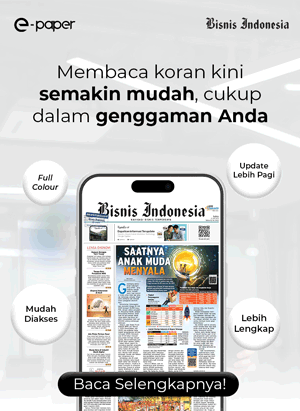Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berkomitmen dalam mengatasi persoalan pengelolaan sampah termasuk polusi plastik. Produsen akan diwajibkan mengumpulkan, mengolah, mendaur ulang, hingga memusnahkan limbah plastik dari produk yang dihasilkan sendiri.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan meskipun perundingan Perjanjian Plastik Global dalam pertemuan Intergovernmental Negotiating Committee (INC 5.2) yang berlangsung di Jenewa Swiss pada awal Agustus ini belum mencapai kesepakatan, namun Indonesia menegaskan peran kepemimpinannya dalam upaya global menghentikan polusi plastik. Menurutnya, polusi plastik termasuk mikroplastik merupakan krisis planet yang mengancam lingkungan dan kesehatan masyarakat yang harus segera ditangani bersama.
"Saat ini baru 39% sampah di Indonesia yang terkelola dengan baik, sementara sisanya masih mencemari lingkungan. Kondisi ini mempertegas bahwa polusi plastik telah mencapai tingkat krisis dan tidak bisa ditunda lagi penanganannya," ujarnya dikutip Jumat (22/8/2025).
Adapun aturan ketentuan untuk mewajibkan produsen mengelola sampah plastik atau tanggung jawab produsen yang diperluas (Extended Producer Responsibility/EPR) berpotensi diterbitkan tahun ini dengan implementasi bertahap. Adapun EPR sudah dimandatkan dalam Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, meski kini sifatnya masih sukarela.
"Sekarang sedang diselesaikan peraturan atau instrumennya menjadi wajib dan akan ditetapkan mulai tahun ini dan implementasinya bertahap," katanya.
Untuk diketahui, Kementerian Lingkungan Hidup mengadakan pertemuan dengan para pelaku usaha termasuk yang tergabung di dalam National Plastic Action Partnership (NPAP) dimana dalam pertemuan tersebut EPR sebagai salah satu aspek penting dalam penanganan sampah plastik demi mencapai target pemerintah untuk pengelolaan sampah 100% pada 2029.
Baca Juga
Menurutnya, EPR merupakan kewajiban produsen untuk bertanggung jawab terhadap sampah plastik yang dihasilkan kemasan produknya atau dari hulu ke hilir. Tanggung jawab itu termasuk menarik kembali sampah produknya dan merancang kemasan multiguna sehingga sampah tidak akan berakhir di TPA. Hal ini karena implementasi EPR akan menjadi salah satu faktor penting mewujudkan ekonomi sirkular di Indonesia yang mendorong nilai pengurangan (reduce), penggunaan kembali (reuse), dan daur ulang (recycle).
Namun demikian, pihaknya tak menampik proses pengelolaan sampah plastik ini tak langsung instan karena membutuhkan pendanaan yang besar dan terdapat kebutuhan pengawasan yang lebih ketat dari hulu ke hilir, serta implementasi pengelolaan sampah di tingkat tapak atau permukiman.
"Proses implementasi EPR ini akan bertahap karena perlu melibatkan berbagai pihak tidak hanya kementerian/lembaga lain, seperti Kementerian Perindustrian, lalu ada perbankan, selain juga pihak pemangku kepentingan lain. Kami akan finalisasi rumusan untuk menjadi kebijakan dan instrumen di masing-masing kementerian," ucapnya.
Menurutnya, jika sampah plastik tak ditangani dengan komprehensif, maka akan menimbulkan permasalahan pencemaran lingkungan yang serius lantaran sulit untuk terurai secara alami. Jika pun terurai, maka menghasilkan mikro plastik yang mampu berdampak pada terjadinya pencemaran lingkungan.
Adapun sampah plastik dominan berupa kemasan-kemasan kecil, kemasan wadah, kantong belanja, hingga sedotan dimana produksinya menyumbang sekitar 40% tetapi jumlah yang didaur ulang justru hanya kurang dari 10%. Hal ini menjadi tanggung jawab para produsen plastik untuk memilih kembali kebijakan pengemasan yang dapat didaur ulang.
"Yang pertama, kami akan ketat untuk melakukan penggunaan kembali atau mendaur ulang. Tadi malam sudah bertemu Bapak Menteri Perindustrian untuk membahas langkah kami. Plastik menjadi problematik bagi lingkungan, yaitu sekali pakai. Ini menimbulkan masalah, mengandung bahan berbahaya beracun," tutur Hanif.
Kementerian Lingkungan Hidup per 1 Januari 2025 juga telah menghentikan impor scrap plastik. Lalu upaya meminimalkan penggunaan sampah plastik menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk produsen produk yang masih memanfaatkan plastik sebagai kemasan.
KLH juga tengah menyusun insentif maupun disinsentif bagi perusahaan terkait pengelolaan sampahnya sendiri. Pemerintah menargetkan pengelolaan sampah dapat mencapai 100% pada 2029 termasuk sampah plastik. Upaya yang dilakukan untuk merealisasikan target penyelesaian masalah tata kelola sampah pada 2029 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Investasi yang diperlukan pemerintah untuk mencapai pengelolaan sampah 100% pada 2029 diproyeksikan mencapai sekitar Rp300 triliun.
Investasi tersebut untuk membiayai pembangunan 250 tempat pemprosesan sampah terpadu (TPST) dan lebih dari 42.033 Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) di seluruh Indonesia. Lalu fasilitas modern seperti biodigester, Refuse-Derived Fuel (RDF) dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di 33 kota besar. Selain itu, 550 TPA terbuka atau open dumping saat ini mulai diubah menjadi sanitary landfill atau control landfill.
"Pengembangan fasilitas modern seperti biodigester, refuse derived fuel atau waste to fuel, dan waste to energy telah kami rancang untuk beberapa kota besar yang timbulan sampahnya lebih dari 1.000 ton per hari. Tentu kami sekali lagi membuka ruang kolaborasi dengan semua pihak yaitu pemerintah, akademisi, bisnis, lembaga, pembiayaan, masyarakat dalam mencapai target pengelolaan sampah," terangnya.
Dengan dukungan regulasi yang kuat, ilmu pengetahuan, investasi berkelanjutan, dan partisipasi publik, solusi pengelolaan sampah berkelanjutan akan
lebih efektif dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan yang lebih hijau.
"Menunda penghentian polusi plastik hanya akan memperburuk pencemaran, membahayakan kesehatan, dan menambah beban ekonomi. Indonesia perlu memperlihatkan posisi yang kuat dalam penanganan plastik tidak hanya untuk nasional tapi juga regional Asia Tenggara. Hal ini mengingat sampah plastik yang berakhir di laut tidak hanya menjadi masalah Indonesia tetapi juga negara kawasan," ujarnya.
CEMARI SUNGAI & LAUT
Hanif menuturkan sampah plastik mulai banyak ditemukan terbawa arus di beberapa pantai di Bali dan intervensi segera dilakukan untuk mengurangi tumpukannya. Bocornya sampah ke lautan sendiri merupakan salah satu akibat dari pengelolaan sampah yang tidak maksimal di beragam wilayah. Hal itu mengingat sampah yang terbuang ke lingkungan di berbagai bagian daerah aliran sungai dapat berakhir ke laut dan terbawa arus ke daerah lain, bahkan negara lain.
Dia memberikan contoh bagaimana DAS Ciliwung dengan hulu di wilayah Gunung Gede dan Pangrango di Jawa Barat melewati banyak daerah sampai akhirnya bermuara di Jakarta Utara. Di wilayah yang dilewati Ciliwung, empat kabupaten/kota di antaranya menghasilkan 3.000 ton per hari dengan TPA yang tidak berfungsi optimal.
"Akhirnya sampahnya lari ke sungai, sungai ke laut. Ini kemudian yang harus kita tangani secara mendasar, makanya kebijakan yang kita lakukan penanganan serius di tingkat darat. Namun di laut juga ada legacy atau plastik yang sudah terlanjur di situ yang tetap harus kita tangani," kata Hanif.
Berdasarkan data dalam Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) milik Kementerian Lingkungan Hidup, jumlah timbulan sampah di Indonesia pada 2024 mencapai 46,63 juta ton dan 10,8 juta ton di antaranya adalah sampah plastik. Timbulan sampah plastik di Indonesia meningkat dari 11% pada 2010 menjadi 19,71% pada 2024. Dari jumlah itu, baru 39% sampah plastik yang mampu diolah dengan baik, sisanya ditimbun di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang masih menerapkan sistem pembuangan terbuka (open dumping), dibakar secara terbuka, dan terbuang di ruang terbuka darat dan perairan. Jika tidak ada upaya luar biasa untuk membatasinya, maka diperkirakan pada 2050 jumlah sampah plastik akan mencapai 50% dari seluruh sampah di Indonesia.
Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular Kementerian Lingkungan Hidup Agus Rusli menambahkan pelaku industri makanan dan minuman diharapkan untuk bersama-sama mencari solusi pengurangan limbah plastik berlapis atau multi-layer terutama dari kemasan mi instan yang sulit didaur ulang.
Menurutnya, plastik multi-layer menjadi tantangan besar dalam pengelolaan sampah nasional karena tidak memiliki nilai ekonomi tinggi seperti plastik jenis PET yang banyak dimanfaatkan kembali oleh pelapak dan bank sampah.
"Contohnya bungkus mi instan, sachet sampo, bungkus wafer dan ciki-cikian. Itu semua plastik multi-layer yang sangat sulit diolah karena terdiri dari beberapa lapisan, termasuk alumunium foil," ucap Agus.
Sebagai salah satu produsen mi instan terbesar di Indonesia memproduksi hingga 20 miliar bungkus dalam setahun. Berdasarkan perhitungan KLH, dari total tersebut dihasilkan sekitar 40.000 ton sampah plastik multi-layer dalam setahun yang belum memiliki solusi daur ulang memadai.
"Untuk menghasilkan satu kilogram mi instan saja diperlukan sekitar 500 bungkus. Jadi bayangkan betapa banyak volume yang terkumpul setiap tahunnya, tapi sulit dimanfaatkan kembali," terangnya.
Dia menegaskan pemerintah tidak hanya menyasar produsen besar, tetapi juga berupaya menjangkau pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang banyak memproduksi makanan ringan dalam kemasan plastik multi-layer. Produk-produk seperti wafer dan kudapan ringan banyak dijual bebas di pasar tradisional maupun minimarket, dan dikonsumsi luas oleh anak-anak. Pemerintah tetap berkomitmen untuk menekan limbah plastik tanpa mengorbankan pertumbuhan industri.
"Kami memahami industri kecil dan menengah ini jumlahnya sangat banyak, melibatkan tenaga kerja besar, sehingga pendekatannya tidak bisa represif. Kami harus berhati-hati karena pengurangan plastik berdampak pada pertumbuhan ekonomi," tuturnya.
KLH terus mengampanyekan perubahan gaya hidup masyarakat merupakan elemen kunci dalam upaya pengendalian polusi plastik, selain regulasi dan teknologi pengolahan sampah. Pasalnya, sebagian besar konsumsi plastik di masyarakat bersumber dari kebiasaan sehari-hari yang tidak disadari, seperti penggunaan kantong plastik sekali pakai saat berbelanja di pasar hingga pemakaian produk rumah tangga yang menghasilkan mikroplastik.
Kebiasaan masyarakat yang bergeser ke arah kemudahan dan kepraktisan telah mempercepat akumulasi sampah plastik di lingkungan. Untuk itu, edukasi publik dan kampanye gaya hidup ramah lingkungan perlu diperkuat agar masyarakat ikut berkontribusi secara aktif dalam pengurangan plastik dari sumbernya.
"Kami terus mendorong pembatasan penggunaan plastik sekali pakai melalui regulasi dan penyusunan peta jalan pengurangan sampah oleh produsen. Namun, regulasi saja tidak cukup tanpa dukungan perubahan pola konsumsi masyarakat. Plastik sebenarnya sangat bermanfaat jika digunakan secara bijak dan berkelanjutan. Yang menjadi masalah adalah pola pakai-buang tanpa tanggung jawab. Itu yang harus kita ubah bersama," ujarnya.
Agus menilai rendahnya kesadaran masyarakat akan mikroplastik, yang sebagian besar berasal dari aktivitas rumah tangga seperti mencuci pakaian sintetis dan memakai sabun pembersih wajah berbahan microbeads. Mikroplastik ini, masuk ke saluran air, mencemari laut, dan bisa kembali masuk ke tubuh manusia melalui konsumsi ikan.
Oleh karena itu, pentingnya pendekatan kultural dalam penanganan plastik. kontribusi rumah tangga dalam mengurangi konsumsi plastik menjadi sangat krusial dalam mencapai target nasional pengurangan sampah.
"Kita perlu membangun kembali budaya membawa tas belanja, memakai wadah isi ulang, dan menghindari produk dengan kemasan berlebih. Perubahan gaya hidup ini jauh lebih berdampak jangka panjang," katanya.
KOMITMEN PENGUSAHA
Sementara itu, Ketua Bidang Sustainability dan Social Impact Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Arief Susanto menuturkan pihaknya berkomitmen dalam pengelolaan sampah plastik seiring masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kemasan plastik dalam kehidupan sehari-hari.
Menurutnya, kemasan plastik masih menjadi kebutuhan vital dalam industri makanan dan minuman terutama karena mempertimbangkan aspek keamanan pangan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.
"Plastik ini masih sangat diperlukan oleh konsumen karena terkait dengan keawetan makanan, perlindungan, penyimpanan, dan tentu saja karena harganya masih bisa dijangkau oleh masyarakat luas," ucapnya.
Dia menilai tantangan terbesar saat ini bukan pada penghapusan plastik melainkan bagaimana mengelola sampah plastik secara berkelanjutan. Berdasarkan data dari sekitar 300 kabupaten, total sampah nasional hingga 2024 mencapai sekitar 35 juta ton dan 20% di antaranya adalah sampah plastik.
Sejumlah perusahaan makanan dan minuman yang tergabung dalam GAPMMI telah melakukan berbagai upaya untuk pengelolaan sampah plastik termasuk membentuk industri daur ulang. Saat ini terdapat lebih dari 200 industri daur ulang di Indonesia dengan kapasitas hingga 2,5 juta ton per tahun, namun baru sekitar 800.000 ton yang termanfaatkan secara optimal. GAPMMI mencatat puluhan perusahaan anggotanya telah menyusun peta jalan pengelolaan sampah sesuai amanat Peraturan Menteri LH Nomor 75/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.
"Total ada 21 perusahaan, masih akan terus bertambah lagi, mereka yang telah mendapat pengakuan dari Kementerian LH atas pelaksanaan peta jalan tersebut," katanya.
Kendati demikian, dia menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif yang melibatkan semua pihak dalam ekosistem pengelolaan sampah plastik. Dia mengusulkan konsep extended stakeholder responsibility yang melibatkan industri, pemerintah, masyarakat, akademisi, hingga organisasi non-pemerintah.
"Kami menyadari bahwa pengelolaan sampah plastik bukan hanya tanggung jawab produsen, tetapi juga seluruh stakeholder. Mulai dari edukasi masyarakat, pemilahan sampah dari rumah, hingga perbaikan sistem pengangkutan dan pemrosesan sampah di lapangan harus dilakukan bersama," ucapnya.
Arief berharap ke depan industri makanan dan minuman dapat terus menjadi pemimpin dalam pengelolaan sampah plastik, namun tetap memerlukan dukungan nyata dari seluruh elemen bangsa agar pengendalian sampah plastik bisa berjalan efektif dan berkelanjutan.
KEBIJAKAN HULU KE HILIR
Manajer Kampanye Tata Ruang dan Infrastruktur Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Dwi Sawung berpendapat mewajibkan kebijakan daur ulang saja tidak cukup untuk mengatasi permasalahan sampah plastik karena hanya 9% hingga 12% produk plastik yang dapat didaur ulang.
"Daur ulang saja itu sama sekali tidak cukup karena ada 90% plastik yang diproduksi itu berakhir mencemari lingkungan, dibakar dan menjadi polusi udara, jadi emisi gas beracun, dan jadi mikroplastik yang tercecer ke mana-mana," tuturnya kepada Bisnis.
Pemerintah perlu melarang penggunaan plastik sekali pakai dan mendorong praktik guna ulang sebagai solusi. Saat ini sudah ada lebih dari 100 kabupaten/kota dan provinsi yang melarang penggunaan plastik sekali pakai. Melalui kebijakan pelarangan penggunaan plastik sekali pakai diharapkan ada pengurangan sampah plastik secara signifikan, khususnya pada jenis plastik sekali pakai seperti kantong belanja, sedotan dan styrofoam.
Dia menilai pemerintah perlu membatasi produksi plastik seperti polistirena, styrofoam, sachet, dan tas kresek. Selain itu, perlu ada upaya untuk mendorong bisnis yang lebih ramah lingkungan seperti mengganti kemasan sachet menjadi kemasan lain yang lebih mudah didaur ulang atau mudah terurai oleh alam.
"Pelaku usaha yang terlibat dalam mata rantai plastik baik sebagai material tunggal maupun kemasan produk, dia harus transisi untuk tidak lagi menggunakan jenis plastik tertentu seperti polistirena, sachet, multilayer sachet," ujarnya.
Lalu juga perlu ada penguatan upaya untuk meningkatkan collection rate atau pengumpulan sampah plastik untuk meningkatkan recycling rate Menurutnya, upaya-upaya tersebut harus dilakukan secara beriringan agar penanganan masalah sampah plastik dapat lebih efektif.
"Jadi penanganan sampah plastik ini perlu dilakukan dari hulu ke hilir," katanya.